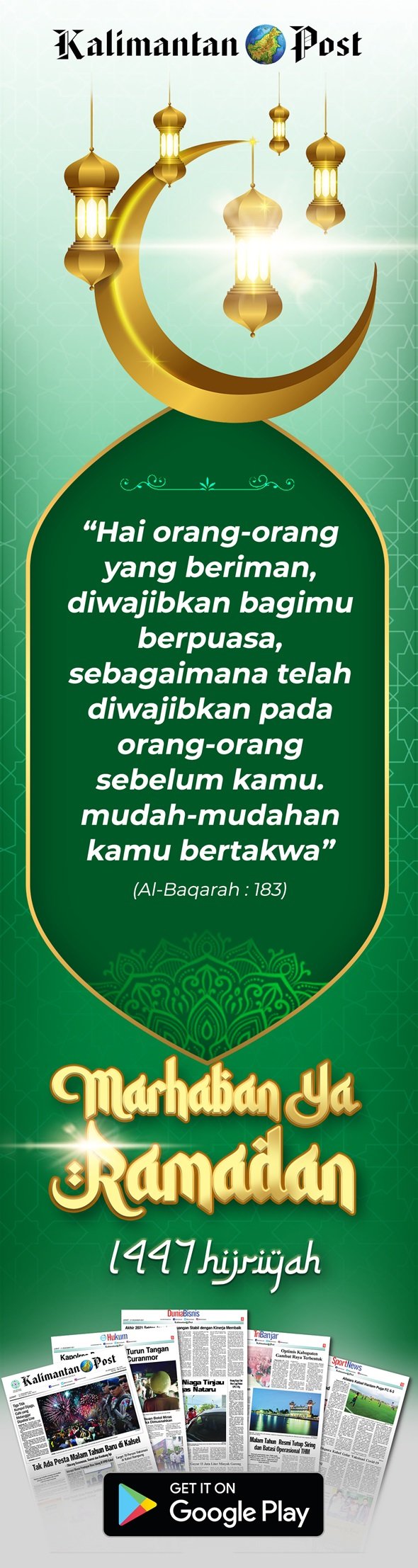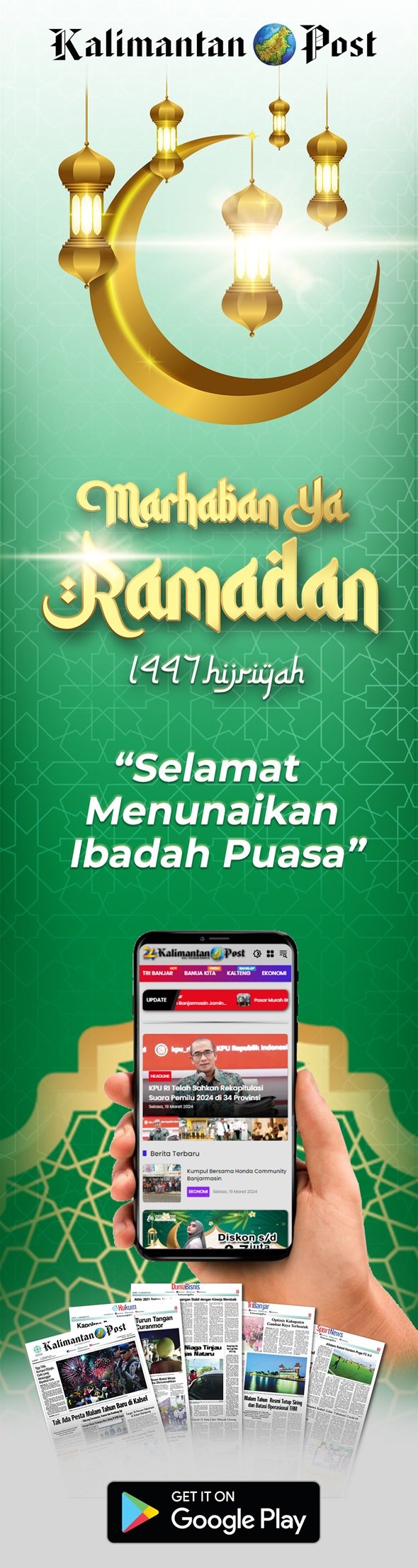Oleh : Hafizhaturrahmah
Aktivis Muda
Indonesia telah lama menjadi panggung utama bagi praktik korporatokrasi—situasi di mana korporasi besar, terutama dari negara maju, memiliki pengaruh dominan atas kebijakan pemerintah. Fenomena ini tidak lahir dalam semalam; ia tertanam dalam sejarah panjang hubungan antara negara berkembang dan investasi asing yang sering timpang. Sejak era Orde Baru, praktik ini mengakar dengan diberlakukannya berbagai kebijakan yang memprioritaskan modal asing atas dalih pembangunan ekonomi. Pertanyaannya adalah, apakah kebijakan ini benar-benar menguntungkan Indonesia, atau justru menciptakan ketergantungan sistemik yang melemahkan kedaulatan ekonomi?
Pada masa Orde Baru, Soeharto membuka lebar pintu investasi asing melalui UU Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Kebijakan ini menawarkan beragam insentif, seperti pembebasan pajak dan jaminan terhadap nasionalisasi aset. Di atas kertas, langkah ini tampak strategis: mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Namun, kenyataannya, keberpihakan terhadap modal asing sering kali mengorbankan pelaku usaha lokal. Seperti yang diungkapkan John Perkins dalam bukunya Confessions of an Economic Hitman, korporatokrasi tidak hanya bertujuan mendorong investasi, tetapi juga menciptakan pola ketergantungan melalui kontrol ekonomi dan politik.
Akibatnya, Indonesia kehilangan posisi tawar dalam bernegosiasi dengan perusahaan multinasional. Misalnya, Freeport-McMoRan, yang mengelola tambang emas dan tembaga di Papua, menjadi simbol dominasi korporasi asing. Meski memberikan kontribusi ekonomi, pengelolaannya sering dikritik karena lebih menguntungkan pihak asing daripada rakyat Indonesia. Dengan dalih efisiensi, kepentingan rakyat lokal kerap terpinggirkan, baik dari segi pembagian keuntungan maupun pelestarian lingkungan.
Tantangan utama dalam menghadapi korporatokrasi adalah menemukan keseimbangan antara menarik investasi asing dan melindungi kepentingan nasional. Kebijakan liberalisasi ekonomi yang diadopsi Orde Baru bertumpu pada ide bahwa modal asing akan menjadi katalisator pembangunan. Namun, model ini sering kali mengabaikan pelaku usaha kecil, menengah, dan koperasi (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.
Kritik serupa muncul dalam pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, yang menghapus pembedaan signifikan antara investor asing dan domestik. Meski bertujuan menciptakan iklim investasi yang kompetitif, kebijakan ini memperlebar jurang ketimpangan ekonomi. Pelaku usaha lokal kerap kalah bersaing dengan korporasi asing yang memiliki sumber daya melimpah.
Data dari Kementerian Investasi menunjukkan bahwa investasi asing langsung (Foreign Direct Investment, FDI) menyumbang 55% dari total investasi di Indonesia pada 2023. Meski angkanya besar, kontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan masyarakat belum optimal. Alih-alih menjadi katalisator pembangunan inklusif, FDI sering kali menimbulkan permasalahan sosial, seperti konflik lahan, degradasi lingkungan, dan pelanggaran hak asasi manusia.
Menghadapi tantangan ini, Indonesia membutuhkan pendekatan yang lebih strategis dan berkeadilan. Ada tiga pilar utama yang harus diperkuat: kebijakan, partisipasi masyarakat, dan inovasi teknologi.
- Kebijakan yang Berdaulat dan Berkeadilan. Pemerintah harus merevisi kebijakan investasi untuk memastikan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal. Salah satu langkah konkret adalah memperketat regulasi terkait corporate social responsibility (CSR) dan pembagian keuntungan dengan masyarakat lokal. Dalam kasus Freeport, renegosiasi kontrak karya pada 2018 yang meningkatkan porsi saham Indonesia menjadi 51% merupakan langkah positif. Namun, pendekatan serupa harus diterapkan secara konsisten untuk semua investasi asing.
- Pemberdayaan UMKM sebagai Pilar Ekonomi Nasional. Pemberdayaan UMKM merupakan kunci untuk mengurangi ketergantungan pada modal asing. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang 61% dari PDB nasional. Namun, akses terhadap pembiayaan dan pasar global masih menjadi hambatan. Pemerintah perlu meningkatkan akses permodalan dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing UMKM.
- Penguasaan Teknologi sebagai Basis Kemandirian. Era digital memberikan peluang besar untuk mengurangi ketergantungan pada investasi asing. Teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi dan ekspansi pasar. Misalnya, pemerintah dapat mendorong kolaborasi antara pelaku usaha lokal dan institusi riset untuk menciptakan produk inovatif yang berdaya saing tinggi.
Dari sudut pandang agama, eksploitasi sumber daya tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat bertentangan dengan prinsip keadilan. Dalam Al-Qur’an, Surah Al-Baqarah ayat 188 menyebutkan, “Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil.” Ayat ini mengingatkan pentingnya distribusi ekonomi yang adil. Selain itu, konsep maslahah dalam Islam menekankan bahwa kebijakan publik harus membawa manfaat bagi sebanyak mungkin orang.
Sebagai tambahan, teori dependency dari Andre Gunder Frank menyoroti pentingnya memutus ketergantungan ekonomi pada negara maju. Indonesia harus bergerak dari posisi sebagai negara perifer menjadi pemain utama di panggung global.
Mengatasi warisan korporatokrasi bukanlah tugas yang mudah, tetapi bukan pula hal yang mustahil. Dengan mengutamakan keberpihakan terhadap pelaku usaha lokal, mengadopsi teknologi, dan menerapkan kebijakan yang berkeadilan, Indonesia dapat membangun ekonomi yang mandiri dan berkelanjutan. Seperti yang pernah dikatakan Bung Hatta, “Indonesia merdeka bukanlah akhir, melainkan alat untuk mencapai kehidupan yang adil dan makmur.” Semangat ini harus terus menjadi landasan perjuangan kita dalam menghadapi tantangan globalisasi dan hegemoni ekonomi.
Hanya dengan kemandirian, Indonesia dapat memastikan bahwa pembangunan tidak hanya menjadi milik segelintir pihak, tetapi benar-benar membawa manfaat bagi seluruh rakyatnya.